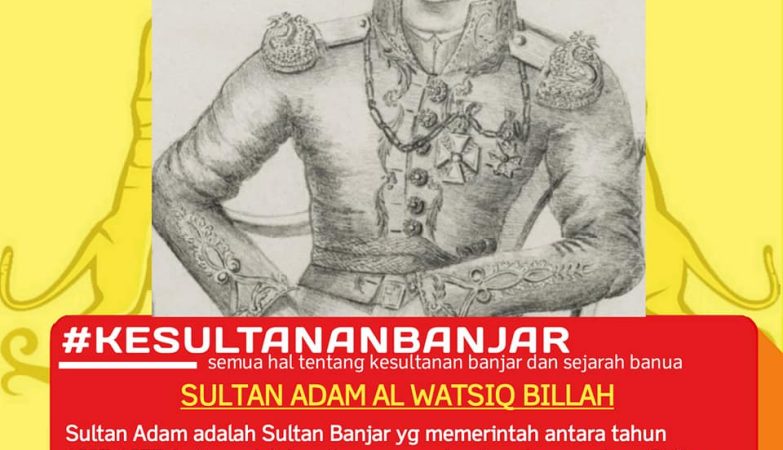Prof. Helius Sjamsuddin, Ph.D, M.A.
Sejarawan Nasional (Pakar Sejarah Banjar)
Pada dasawarsa terakhir abad ke-20 dan/atau dasawarsa pertama abad ke-21 kita semua menyaksikan semacam “gerakan” kehadiran kembali puluhan—kalau bukan ratusan—kerajaan/kesultanan di Indonesia dengan sebutan“Kesultanan Nusantara” yang raja-raja/sultan-sultannya berhimpun dalam sebuah forum silaturahim bersama. Wujud luarnya berupa pertemuan dua tahun sekali secara bergilir dalam bentuk Festival Keraton Nusantara (FKN).
 Fenomena ini dapat kita tempatkan dalam kajian fenomenologi (dari kata Yunani: phainomena, kesadaran) dengan salah satu variannya politik identitas (identity politics). Sebagai kajian akademik fenomenologi adalah multi-disiplin; ia merambah ke berbagai bidang, sejak dari estetika seni, sastra, tari, drama/teater, musik, film, sampai ke arsitektur, hukum, komunikasi, biografi, pendidikan, gender, psikologi, etnisitas/etnologi, ekologi, sampai kepada metode penelitian kualitatif, politik dan agama. Sebagai salah satu bidang filsafat, fenomenologi berpengaruh besar pada abad ke-20 bahkan memasuki abad ke-21 ini. Begitu juga dengan politik identitas yang mengait pada kesamaan bahasa, pakaian, adat-istiadat, kelompok/golongan, etnis, bangsa, dll yang menjadi kajian dari disiplin-disiplin sosiologi, sosiologi sejarah, antropologi sosial, psikologi, sejarah, politik. Sederhananya, jika fenomenologi berusaha mengkaji dan memaknai setiap pengalaman individual/kelompok (individual/collective memory), tindakan-tindakan, pikiran, perasaan, ingatan, yang dapat diamati maupun yang masih menjadi cita-cita (ideal), maka politik identitas mengkaji dan mencoba memahami identitas diri yang menjadi pembeda dengan kelompok lain. Fenomenologi, terutama fenomenologi hermeneutika (dan identitas politik) mencoba memaknai mengapa dan bagaimana hadir kembali pengalaman (ecountering) semacam itu. Di Indonesia umumnya diartikan, antara lain, sebagai ”kearifan lokal” (local wisdom).
Fenomena ini dapat kita tempatkan dalam kajian fenomenologi (dari kata Yunani: phainomena, kesadaran) dengan salah satu variannya politik identitas (identity politics). Sebagai kajian akademik fenomenologi adalah multi-disiplin; ia merambah ke berbagai bidang, sejak dari estetika seni, sastra, tari, drama/teater, musik, film, sampai ke arsitektur, hukum, komunikasi, biografi, pendidikan, gender, psikologi, etnisitas/etnologi, ekologi, sampai kepada metode penelitian kualitatif, politik dan agama. Sebagai salah satu bidang filsafat, fenomenologi berpengaruh besar pada abad ke-20 bahkan memasuki abad ke-21 ini. Begitu juga dengan politik identitas yang mengait pada kesamaan bahasa, pakaian, adat-istiadat, kelompok/golongan, etnis, bangsa, dll yang menjadi kajian dari disiplin-disiplin sosiologi, sosiologi sejarah, antropologi sosial, psikologi, sejarah, politik. Sederhananya, jika fenomenologi berusaha mengkaji dan memaknai setiap pengalaman individual/kelompok (individual/collective memory), tindakan-tindakan, pikiran, perasaan, ingatan, yang dapat diamati maupun yang masih menjadi cita-cita (ideal), maka politik identitas mengkaji dan mencoba memahami identitas diri yang menjadi pembeda dengan kelompok lain. Fenomenologi, terutama fenomenologi hermeneutika (dan identitas politik) mencoba memaknai mengapa dan bagaimana hadir kembali pengalaman (ecountering) semacam itu. Di Indonesia umumnya diartikan, antara lain, sebagai ”kearifan lokal” (local wisdom).
Dilihat dari kacamata modern, “gerakan-gerakan” semacam di atas dianggap sudah atavistik-obsolet. Sebaliknya dari kacamata postmodern dalam era di mana kita sekarang hidup ini adalah sebuah gerakan budaya dengan segala aspek pada umumnya. Ia menjadi luar biasa ketika “orang-orang” istana, keraton, dalem menjadi pusat, pelindung dan penggerak utamanya (maecenas dan prime mover). Sebenarnya ini juga tidak aneh karena dahulupun kesultanan (keraton) selain sebagai pusat kekuasaan juga menjadi pusat budaya: istana adalah representasi dari seluruh wilayah dan kawulanya. Setelah 66 tahun kita semua menjadi anak-anak bangsa dari sebuah negara-bangsa (NKRI), ketika kita semua masih mencari-cari karena belum melihat wujud yang pasti, nyata, dan pas dari sebuah budaya nasional yang kita semua cita-citakan, maka kita menoleh kembali ke sejarah: apakah ada dari artefak-artefak verbal dan/atau non-verbal yang bersisa yang kita semua sebut “kearifan lokal”. Ratusan etnis di Indonesia memiliki ratusan kearifan lokal yang masih tersimpan masing-masing dalam khasanah budaya-budaya lokal. Indonesia sebagai negara-bangsa yang multi-kultural, orang-orang mulai melihat sisi lain dari keping uang yang sama dari apa yang disebut dengan “pendidikan perbedaan” (diversity education), “ethno-pedagogy” yang sebenarnya bermuara juga pada toleransi menghargai perbedaan-perbedaan sebagai anak-bangsa dari sebuah negara-bangsa.
Dalam format seperti itulah kita melihat kehadiran Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar. Ia mengemban tugas berat pelastarian budaya Banjar (budaya dalam arti luas) yang menurut orang-orang Banjar yang arif patut dilestarikan dan diwariskan. (Kata “lestari” dan “waris” jangan diartikan statis melainkan dinamis). Oleh sebab itu adalah wacana yang sangat meletihkan jika keberadaan lembaga semacam ini menimbulkan pro-kontra, apalagi “membenturkan” gerakan kebangkitan kesultanan-kesultanan di Indonesia ini dengan negara nasional. Saya sendiri melihat kebangkitan Kesultanan Banjar ini sebagai sebuah metafora—mempunyai nilai simbolik selain nyata tentu saja—yang mencoba menjadi perekat bagi orang-orang Banjar melalui adat-budaya Banjar yang khas.
Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, di kepulauan Nusantara terdapat puluhan kalau bukan ratusan kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan, sejak yang berukuran liliput sampai yang berukuran raksasa. Banjar adalah salah satu Kesultanan Islam yang besar dan berjaya di Kalimantan. Ketika pendiri dinasti Sultan Suriansyah berhasil meletakkan dasar-dasar kekuasaannya di Kalimantan tahun 1520-an, perahu-perahu dagang Banjarmasin sudah muncul antara lain di Banten tahun 1596. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kampung-kampung Banjar dengan pemukim-pemukimnya muncul di bandar-bandar besar Nusantara di samping kampung-kampung Bugis, Melayu, Jawa dll. Identitas Banjar dan Islam tetap mereka pertahankan. Sewaktu bangsa-bangsa Barat datang—apakah itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dll—mereka berseberangan dengan kesultanan Islam Banjarmasin. Ketika di pusat pemerintahan Banjarmasin terjadi intrik-intrik istana memperebutkan kekuasaan dan salah satu partai meminta bantuan asing, maka dari situlah awal keruntuhan keraton Banjarmasin. Dinasti yang dibangun dengan susah payah oleh Sultan Suriansyah terpisah-pisah dalam jurai-jurai yang saling berseberangan. Resistensi panjang terhadap dominasi asing yang memancing di air keruh akhirnya tidak dapat dibendung. Kesultanan Banjar berakhir tragis dan tinggal menjadi kenang-kenangan sejarah sementara jurai-jurai keturunan Sultan Suriansyah terpencar-pencar ke mana-mana, ada yang masih diketahui keberadaannya, ada pula yang hilang dalam catatan sejarah. Ini pembelajaran sejarah yang amat berharga bagi kita semua!
Keruntuhan tragis keraton Banjar yang oleh sejarawan Belanda E.B. Kielstra ditulis dengan panjang lebar dalam “De ondergang van het Bandjermasinsche Rijk” memberi pembelajaran sejarah yang amat berharga bagi keturunan-keturunan dari jurai-jurai yang dahulu bertikai. Semangat kesadaran inilah dapat kita baca dalam Berkhidmat untuk Tahta Budaya. Sebuah cita-cita mulia kita kutip seluruhnya sebagai berikut:
… satu langkah awal untuk merekatkan kembali tali silaturahmi para zuriat…. Dimulai dari raja pertama Kesultanan Banjar abad ke-15 [16] (zaman Islam) Sultan Suriansyah hingga generasi sekarang awal abad ke-21. Semenjak Kerajaan Banjar dihapuskan oleh kolonial Belanda, ikatan kekerabatan itu menjadi sangat renggang. Antara kerabat bisa saling tidak mengenal, acuh tak acuh dan terjebak pada persaingan yang tidak perlu, bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Khairul sadar betul bahwa melestarikan budaya, adat dan tradisi Kerajaan Banjar adalah kerja bersama para zuriat.
Silsilah seharusnya tidak menjadi cikal bakal perpecahan dan pertarungan ego individu. Persatuan dan kesatuan adalah nilai kearifan lokal masyarakat Banjar yang ada sejak dahulu kala. Ini juga diwariskan oleh kerabat kerajaan dengan ikatan silsilah. Perpecahan adalah warisan masa kolonial yang mencemari nilai kearifan lokal.
Harapan besar yang ada di benak Khairul Saleh bahwa suatu ketika seluruh zuriat Kesultanan Banjar bersatu-padu mengangkat harkat martabat keluarga dan masyarakat Banjar di bidang budaya, adat dan tradisi.
Berkaitan dengan di atas, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar ini, pertama internal, kedua eksternal. Pertama (internal), ini sebuah momentum terbaik untuk mempererat silaturahmi kekerabatan seluruh jurai kesultanan, dengan Khairul Saleh sebagai mediator. Sebenarnya beberapa teladan yang telah dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya sebagai bentuk “kearifan lokal”—sengaja atau kebetulan:
- Sultan Sulaiman telah memberi teladan ketika ia menampung putra Pangeran Amir yang diasingkan ke Sri Lanka, Pangeran Mas’ud, di dalem Martapura, bahkan menikahkan putrinya Khadijah, saudara dari Sultan Adam, dengan Pangeran Mas’ud;
-
Sultan Sulaiman menikahkan Pangeran (Panembahan) Antasari dengan Ratu Antasari, saudara dari Sultan Muda Abdul Rakhman, yang melahirkan Gusti (Panembahan) M. Said;
-
Sultan Adam melindungi Pangeran Antasari dalam keraton bahkan memberikan tanah apanage di Mangkauk.
-
Sultan Adam menikahkan putranya Raja Muda Abdul Rakhman dengan saudara perempuan Antasari, Ratu Abdur Rakhman.
-
Hidayatullah yang dinobatkan sebagai Sultan oleh tetuha Amuntai—tanpa persetujuan Belanda–telah bahu membahu dengan Pangeran Antasari dalam Perang Banjar;
-
Penamaan alun-alun Martapura dengan Putri Zalecha—jika yang dimaksud adalah Gusti Zaleha, putri Sultan Seman yang menikah dengan Gusti M. Arsyad, putra Panembahan M. Said;
-
Dalam rangka kerakatan kekerabatan ini, pengakuan pada “pemerintahan darurat” Hidayatullah bersama Antasari, kemudian dilanjutkan oleh Pegustian di Beras Kuning. Jika kita melihat sejarah dari dalam (history from within), para pejuang waktu itu tidak mengakui penghapusan sepihak Kesultanan Banjarmasin oleh Belanda pada bulan Juni 1860. Hidayatullah dengan Antasari, kemudian Antasari bersama-sama putra-putranya membentuk pemerintah Pegustian, mula-mula di hulu Muara Teweh, kemudian setelah Antasari wafat, dilanjutkan oleh kedua putranya, Panembahan M. Said dan Sultan M. Seman di Beras Kuning, Sungai Menawing. Pegustian merupakan representasi “replika” keberlanjutan keraton Banjarmasin yang dihapuskan Belanda.
-
Siapa yang dapat melakukan tentu saja seluruh jurai dari Sultan Suriansyah yang masih hidup sekarang ini. Jika bisa dianggap bahwa Kesultanan Banjar sekarang (2010) adalah lanjutan dari keraton Beras Kuning yang berakhir tahun 1905, bukan keraton yang dihapus Belanda tahun 1860, maka kevakuman keraton Banjarmasin bukan lagi 151 tahun melainkan 105 tahun. Sultan Khairul Saleh dapat melanjutkan kearifan yang telah ditunjukkan oleh Sultan Sulaiman dan Sultan Adam— yang nota bene leluhur Sultan. Ini benar-benar kearifan local in practice! Ini merupakan sebuah narasi keberlanjutan.
Kedua—simbolik sekaligus real–tahta budaya dari kesultanan Banjar yang baru sekarang ini adalah benar-benar juga “tahta untuk rakyat”. Meminjam metafora nautika klasik, Sultan Khairul Saleh sebagai nakhoda, mengemudikan sebuah Banawa Banjar yang besar ini mengangkut seluruh rakyat dan budayanya melayari samudera luas—gelombang kadang-kadang teduh tapi bisa juga bergolak–menuju bandar yang ingin dituju dengan selamat sejahtera. Semoga.